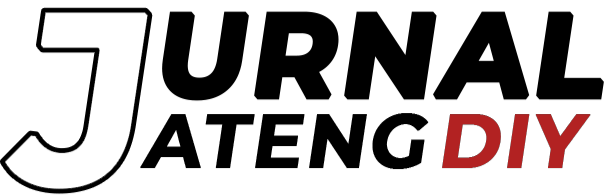Cerpen oleh Noeryoso
Jurnaljatengdiynews.com- Magelang – Tinggal dua kantong lagi, Kang!” bisik Laila sambil berjalan berjingkat menuju pintu sebuah gubuk di pinggir kali. Telapak kakinya yang tanpa alas melangkah hati-hati agar tak mengagetkan pemilik gubuk, juga supaya kedatangannya tak diketahui siapa pun. Setelah meletakkan sebuah kantong plastik di depan pintu gubuk Darsem, Laila segera bergegas kembali ke tempat Qodar menunggunya.
Sayup-sayup takbir berkumandang dari kejauhan. Di masjid kampung mereka, suara takbir sudah berhenti sejak tadi—mungkin para remaja masjid kelelahan setelah mengumandangkannya sejak sore.
Saat melewati jalan setapak di dekat kuburan, hampir saja Laila dan Qodar kepergok peronda. Untungnya, tanaman puring yang tumbuh liar di kuburan itu segera menyembunyikan tubuh mereka. Cukup lama mereka berjongkok di balik gerumbulan puring, menunggu peronda pergi. Tampaknya, kedua peronda sempat melihat bayangan mereka, tetapi tak cukup berani masuk ke dalam area kuburan untuk mengejar.
Laila dan Qodar sebenarnya bisa saja mengambil jalan yang lebih aman, melewati depan rumah Pak RT. Namun, mereka tak ingin ketahuan oleh siapa pun, sehingga memilih jalan setapak di samping kuburan untuk menuju rumah Yitno, lelaki buta yang sehari-harinya mengemis di pasar.
Lamat-lamat, suara pukulan tiang telepon tiga kali terdengar, pertanda waktu telah menunjukkan pukul tiga dini hari. Saat Laila dan Qodar tiba di rumah mereka—sebuah gubuk kecil yang lebih mirip kandang kerbau—bunyi jengkerik seketika berhenti, seolah terkejut oleh derit pintu yang terbuka.
Laila segera merebahkan tubuhnya di atas lincak bambu, melepas kerudungnya. Wajahnya yang bulat purnama penuh peluh. Sementara itu, Qodar mengambil dua gelas minum, menuangkan teh sisa berbuka, lalu menyodorkannya kepada Laila sebelum meneguk miliknya hingga tandas.
“Terima kasih, Kang,” ucap Laila, bangkit dari rebahannya dan menghabiskan teh manis yang sudah dingin itu.
“Akhirnya selesai juga. Sisa untuk kita cuma ini, Kang,” sambungnya, mengeluarkan beberapa barang dari kardus kecil—sebongkah beras, seplastik kecil gula, sebungkus teh, tepung, minyak, dan beberapa bungkus mi instan.
Qodar hanya tersenyum memandangi barang-barang tersebut. “Maafkan aku, Laila. Tidak seharusnya aku mengajakmu hidup seperti ini,” ucapnya pelan, sudut matanya berkaca-kaca menahan kesedihan.
“Sudahlah, Kang. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk membantu tetangga menyambut Lebaran,” balas Laila sambil menghapus air mata Qodar yang mulai menetes.
Qodar menarik napas dalam. “Bagaimana kalau tahun depan kita ikut i’tikaf di masjid saja?”
“Berarti kita tidak mengamen lagi, Kang? Lalu, bagaimana dengan Mbok Darsem, Pak Yitno, Kang Slamet, Ciput, dan adik-adiknya? Apa kita biarkan mereka berlebaran tanpa kebahagiaan?” tanya Laila, meletakkan biola dan gitar mereka. Sejak remaja, Laila memang mahir bermain biola, sementara Qodar pandai memetik gitar.
“Apa kamu tidak ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, seperti mereka yang sedang beri’tikaf di masjid?”
Laila tidak menjawab. Ia justru berseru kegirangan sambil memperlihatkan amplop kecil di tangannya. “Kang! Lihat ini!” serunya.
“Rupanya ada orang yang menyelipkan amplop ini ke ranselku. Mungkin gadis yang kemarin duduk di samping kita saat mengamen.”
“Berapa isinya?” tanya Qodar penasaran.
“Lima ratus ribu!” seru Laila girang.
Namun, Qodar masih tampak ragu. “Laila, apakah kita akan terus mengamen saat orang-orang tengah khusyuk tarawih, hanya agar bisa membagikan bingkisan Lebaran kepada mereka?”
“Kita memang miskin, Kang. Tapi mereka jauh lebih miskin dari kita. Kapan lagi kita bisa meringankan hidup mereka?” jawab Laila mantap.
Qodar hanya terdiam. Sejak menikah, malam-malam Ramadan mereka dihabiskan dengan mengamen, mengumpulkan uang untuk membeli bahan sembako dan membagikannya kepada tetangga-tetangga yang melarat.
“Alhamdulillah, hasil mengamen tahun ini lebih banyak dari biasanya, Kang! Bukan hanya cukup untuk sembako, tapi juga sarung dan baju. Mereka pasti senang melihat bingkisan tergeletak di depan gubuk mereka,” ujar Laila, bersandar penuh kasih sayang di lengan Qodar.
“Kapankah kita diberi momongan, Kang?” bisiknya pelan.
“Mungkin Allah belum melihat kita siap menerima amanah itu, Laila. Atau mungkin, Allah ingin kita menganggap Ciput, Tarmi, dan Godril sebagai anak-anak kita. Bukankah selama ini kita telah mencukupi pangan mereka?” jawab Qodar, membelai rambut Laila dengan lembut.
Laila tergugu menahan tangisnya.
“Apakah mengamen juga bisa membuat kita mendapatkan Lailatul Qadar, Laila?” tanya Qodar kembali.
Laila tersenyum kecil. “Entahlah, Kang. Yang jelas, Kang Qodar sudah mendapatkan Laila. Dan Laila telah mendapatkan Qodar.”
Qodar pun tertawa. Namun, tiba-tiba ia menghentikan tawanya, memberi isyarat kepada Laila agar diam. Bunyi jengkerik di luar rumah mendadak terhenti—tanda ada sesuatu yang mendekat. Tapi, tak terdengar suara langkah kaki sedikit pun. Mungkin suara itu tertindih oleh adzan Subuh yang baru saja berkumandang dari masjid kampung mereka.
“Sudah adzan Subuh, Kang! Ayo ke masjid!” ajak Laila, mengambil mukena. Qodar pun segera menyusul mengambil pecinya.
Namun, ketika mereka membuka pintu, sepasang suami istri itu terbelalak kaget.
Di depan gubuk mereka, tergolek sebuah kardus berisi bayi mungil dengan kulit masih merah. Di samping bayi itu, ada botol minum dan secarik kertas bertuliskan “Lailatul Qadar”.
Melihatnya, Laila segera menggendong bayi itu, mendekapnya penuh kasih sayang. Diciuminya pipi mungil itu dengan suka cita, sementara Qodar hanya menatap takjub.
Malam itu, mereka tak hanya menemukan kebaikan dalam setiap langkahnya, tetapi juga sebuah berkah yang tak terduga—sebuah hadiah dari malam penuh kemuliaan.
Diambil dari buku kumpulan cerpen berjudul Anyelir Merah Putih.